Edukasi Reaksioner
EDUKASI REAKSIONER
Oleh
M.
Luthfi Ersa. F
Di
Hari Pendidikan Nasional ini saya berpikir kira-kira apa yang bisa saya
refleksikan di tengah apa-apa yang jadi perbincangan di dunia pendidikan kita
saat ini. Tentunya, di luar objek pembahasan yang memang sudah sering menjadi
kritik, tidak asyik rasanya kalau hanya sekedar merepetisi menyampaikan soal
yang sudah-sudah. Ternyata, ada satu problem sosiologis yang menggelitik saya
untuk berpikir, yakni terkait keinginan pemangku kebijakan menjadikan
pendidikan sebagai upaya pemecahan setiap masalah sosial. Tindakan yang sangat
etis dan taktikal mungkin, tapi problem bukan di situ. Problem yang muncul ada
di cara pandang melihat fenomena sebagai suatu masalah sosial yang selalu
dianggap “urgent” dan harus segera cepat-cepat, secepat-cepatnya dituntaskan.
Massif dan Reaktif
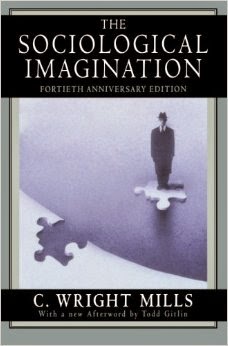 C.
Wright Mills adalah seorang sosiolog yang memiliki alat bantu teoritik yang
membantu kita untuk dapat memilah fenomena seperti apa yang dapat dikategorikan
sebagai masalah sosial dengan apa yang disebut dengan Sociological Imagination. Konsep Personal Trouble dan Public
Issue menjadi penting di sini. Secara sederhana, bila ada 500 murid di
dalam satu sekolah, bila yang terlambat hanya 1-10 orang, itu bukan masalah
sosial, melainkan Personal Trouble
atau masalah personal kesepuluh anak itu. Lain hal nya bila dari 500 murid,
hingga 200 anak terlambat, itu akan menjadi Public
Issue yang mendorong untuk dicarikan
jalan keluarnya, mengkoreksi jam masuk sekolah yang ternyata terlalu pagi,
misalnya. Metode ini tentu bisa saja diterapkan untuk melihat masalah-masalah
sosial terkait pendidikan.
C.
Wright Mills adalah seorang sosiolog yang memiliki alat bantu teoritik yang
membantu kita untuk dapat memilah fenomena seperti apa yang dapat dikategorikan
sebagai masalah sosial dengan apa yang disebut dengan Sociological Imagination. Konsep Personal Trouble dan Public
Issue menjadi penting di sini. Secara sederhana, bila ada 500 murid di
dalam satu sekolah, bila yang terlambat hanya 1-10 orang, itu bukan masalah
sosial, melainkan Personal Trouble
atau masalah personal kesepuluh anak itu. Lain hal nya bila dari 500 murid,
hingga 200 anak terlambat, itu akan menjadi Public
Issue yang mendorong untuk dicarikan
jalan keluarnya, mengkoreksi jam masuk sekolah yang ternyata terlalu pagi,
misalnya. Metode ini tentu bisa saja diterapkan untuk melihat masalah-masalah
sosial terkait pendidikan.
Setidaknya
dari pengalaman saya sekolah hingga setelah lulus kuliah, saya melihat
langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi segala selalu bertendensi
untuk “pukul rata”. Tentu kita dapat mempertanyakan metode seperti apa
sebetulnya yang diterapkan para pemangku kebijakan baik di Senayan dan
Kemendikbud. Saya akan beri contoh nyatanya yang kemungkinan besar para pembaca
sekalian sudah tahu juga.
Persoalan Lingkungan
Masih
ingat kah kita untuk menyerukan kesadaran lingkungan kepada para murid di
sekolah, Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang kemudian ditafsir dengan
sangat lucu sekali oleh sekolah: Murid di awal/akhir masa sekolah mereka wajib membawa
beragam pot tanaman untuk ditanam di sekolah atas nama “penghijauan” dan
“reboisasi” di sekolah? Atau, tidak kah kita sedikit memperhatikan bahwa cukup
banyak sekali sekolah yang dicat dengan warna hijau? Sungguh simbolik sekali
alasannya sebagai pendorong konsep Green
School. Dan, di ruang kelas, secara substansial, dibuatkan mata pelajaran
PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) yang waktu itu pun saya dapatkan sejak 2007
dan, belum ada bukunya, tapi ada guru pengampunya. Nah!
Persoalan Moral
Setiap
kali ada persoalan kenakalan remaja atau segala macam bentuk delikuensi terkait
murid, pasti selalu didefinisikan sebagai “Degradasi Moral”. Sedangkan, yang
lucu adalah anak menyontek/berbuat curang ketika UN ya dibiarkan saja agar
tingkat kelulusan tinggi, agar nama sekolah tidak tercoreng. Sungguh politis.
Yang
lebih menarik perhatian adalah keputusan untuk menambah jam mata pelajaran
Agama di kelas. Menambah hal-hal yang berbau Agamis di ruang-ruang kelas.
Bahkan ini mulai dilestarikan lewat kurikulum, K1 di dalam badan struktur
Kurikulum 2013 yang berbunyi “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya” adalah bukti nyata.
Persoalan Multikultural
Kekerasan
etnis yang tak kunjung selesai, fenomena kekerasan antar umat beragama pasca
reformasi mendorong pemerintah untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa
masyarakat kita tidak memahami keberagaman, sehingga, melalui pendidikan,
lagi-lagi kepada murid di sekolah, dianggap butuh ada penambahan mata pelajaran
yang sekiranya bisa mengcover kesadaran tentang keberagaman di dalam
masyarakat. Pada akhirnya terselip di mata pelajaran sosiologi dalam satu bab
sendiri yaitu “Masyarakat Multikultural”.
Menurut
saya pun tidak ada salahnya, yang menjadi masalah teknisnya, bagaimana
menerjemahkan definisi Multikulturalisme itu sendiri. Bagaimana menjelaskan
perbedaan Multikultural dengan Plural? (di level bangku perkuliahan pun hal-hal
ini secara subtil masih terus diperbincangkan dan diperdebatkan) juga,
bagaimana guru menciptakan suatu strategi pembelajaran yang tidak hanya
menghafal tetapi juga menimbulkan kesadaran tentang keberagaman di ruang kelas
bila anak didiknya saja masih senang bersikap primordial dengan identitas
keberagamaannya dan klub-klub sepak bola pilihannya?
Persoalan Seksualitas
Belakangan,
banyak sekali penelitian maupun tindakan-tindakan praktis menyoal pendidikan
seksual. Ini lebih problematik. Pemerintah akan sangat reaktif terhadap kasus
pelecehan seksual (yang barangkali baru mereka sadari setelah melihat dari beragam media massa dan kemudian
diklaim sebagai fenomena gunung es). Untuk itu lah mereka berupaya
menyelesaikan masalah ini dengan membuat kebijakan di atas kertas bahwa sekolah
harus mengadakan pendidikan seksual di ruang kelas.
Karena
terlalu reaktif, mereka lupa bahwa bahwa realitas chit-chat tentang seksualitas masih merupakan hal tabu, bahkan di
ruah (entah karena benar-benar karena unsur ketidaktahuan atau memang sengaja
tidak diperbincangkan karena urusan “moral”, entah). Pun, dalam ragam seminar
di sekolah, yang ikut hanya perwakilan-perwakilan siswa. Lantas, bagaimana
konstruksi pengetahuan terkait seksualitas bisa berjalan dengan mulus?
Persoalan Buta Huruf
Penelitian
skripsi saya mengenai hal ini. Persoalan buta huruf jelas merupakan masalah
sosial. Yang menarik, buta huruf merupakan masalah sosial yang sudah sangat
karatan dan usang. Ini yang menjadi fokus penelitian saya, saya penasaran,
bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah sosial yang umurnya melebihi ulang
tahun kemerdekaan Indonesia ini? Lantas, hasil data yang saya temukan?
Menyedihkan. Mereka tidak memiliki formulasi yang pas selain program kejar
paket, program baca-tulis dan program pemberdayaan (Pembaca bisa bayangkan,
bahkan output urusan teknis tentang
baca-tulis diarahkan menjadi entrepreneur yang memiliki economic value). Bahkan saya menafsir itu bukan lah program
melainkan proyek.
Kelas sebagai Ruang Percakapan
Saya
tentu paham beban tanggung jawab dari mereka sebagai para pemangku kebijakan
pendidikan, tetapi upaya pemecahan masalah sosial dengan pendekatan yang
terlalu dan selalu makro, kaku dan terlalu teknis-administratif dan ditambah,
reaktif justru rasa-rasanya menyulitkan diri mereka sendiri. Ini tentu juga
menjadi sebuah ejekan terhadap kompetensi guru yang ada di kelas, begitu pula
murid-muridnya. Saya selalu bertanya-tanya, mengapa pemerintah tidak pernah
benar-benar memberikan kebebasan bergerak pada dua subjek dalam ruang kelas ini
untuk membicarakan hingga menyelesaikan permasalahan dalam kelas?
Segala
hal-hal negatif yang setidaknya membuat kuping panas di Kemendikbud selalu
langsung didefinisikan sebagai masalah sosial yang harus dengan segera
ditangani, lebih-lebih, penanganannnya sangat tidak saintifik namun moralis.
Kemudian, segala rumusan dan hasil jadi
“rapat” mereka yang dibuat oleh orang-orang yang “itu-itu” juga kemudian
didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai perangkat aplikasi.
Sering
kali, guru dan murid sebagai subjek inti tidak pernah dilibatkan secara
langsung dalam segala rapat rumusan kebijakan. Apakah guru adalah kertas
kosong? Apakah murid adalah kertas kosong?
Tapi,
ya sudahlah…
***
.jpg) Di
Hari Pendidikan Nasional ini, Saya hanya berandai-andai, ada saat di mana para
elit pendidikan selalu datang dan duduk melingkar, mungkin sambil lesehan atau
menyantap gorengan dan menyeruput teh atau kopi bersama guru dan murid,
bercengkrama tanpa harus pakai power point menjelaskan hal-hal teknis
kementerian, tetapi membicarakan soal keseharian mereka di sekolah. Di setiap
sekolah tanpa terkecuali.
Di
Hari Pendidikan Nasional ini, Saya hanya berandai-andai, ada saat di mana para
elit pendidikan selalu datang dan duduk melingkar, mungkin sambil lesehan atau
menyantap gorengan dan menyeruput teh atau kopi bersama guru dan murid,
bercengkrama tanpa harus pakai power point menjelaskan hal-hal teknis
kementerian, tetapi membicarakan soal keseharian mereka di sekolah. Di setiap
sekolah tanpa terkecuali.
Saling
berbicara, berargumen, berhadap-hadapan, Tanpa dibatasi kelas sosial, status
sosial, tua atau muda dan seragam apa yang dipakai..
Saling
berbicara, berargumen, berkeluh kesah, Tanpa takut kehabisan waktu sejam, dua
jam..
Saling
berbicara, berargumen, Tanpa takut dibantah atau disalah-salahkan..
Bukankah
salah satu cara untuk menyelesaikan segala persoalan selalu dimulai dari saling
mendengarkan satu sama lain?
Depok, 2 Mei 2015
Di tengah lantunan lagu “You Belong to
Me” aransemen Tika and The Dissidents



Yah begitu lah.. Zaman sekarang pada banyak manusia yang ngga mau 'kalah', bahkan untuk mendengarkan saja ia tak mampu.. :(
BalasHapusKetidakmampuannya muncul justru dari ketidakinginan mendengarnya sejak awal :)
BalasHapus